BAB 9
‘Usu pernah bertunangkah? Atau
pernah berkahwin?’
Darwisyah berteka-teki sendiri. Dia
terdengar perbualan Nenek Leha dan Usu Roslan kelmarin ketika sedang menunggu
Danish Aniq tiba. Pada mulanya ia hanya
perbualan biasa sahaja yang berkisar tentang jodoh. Langsung tidak menarik minat Darwisyah untuk
mendengar dengan teliti. Tetapi satu
ayat yang keluar dari mulut Nenek Leha menggamit perasaan ingin tahu dalam diri
Darwisyah.
“Aniq, boleh aku tanya kau satu
soalan?”
“Tanyalah,” balas Danish Aniq. Ketika itu mereka sedang berjalan menuju ke
sekolah.
“Usu pernah berkahwinkah sebelum ini?”
lancar soalan yang ditanya oleh Darwisyah. Danish Aniq tampak sedikit terkejut.
“Mengapa kau tanya soalan sebegini kepadaku?”
“Sebab aku tahu kau mesti ada jawapannya!”
bidasnya cepat.
“Apa yang menyebabkan kau yakin aku ada jawapan untuk soalan kau?”
“Sebab kau lebih rapat dengan usu,”
Darwisyah memulangkan kata kepada soalan saudaranya itu.
“Tapi kau anak saudaranya.”
“Tapi usu seperti menganggap aku bukan anak saudaranya. Dia seperti tidak sukakan aku!” keras suara Darwisyah. Tegas!
Danish Aniq membisu. Entah kenapa
sudut hatinya agak terusik dengan kata-kata Darwisyah yang berbaur luahan hati.
“Kau sudah tanya Nenek Leha tentang usu?”
Darwisyah menggeleng laju. Ruang
matanya kelihatan berkaca. Rasa sebak mula bertapak di ruang hatinya.
“Aku rasa lebih baik kau tanya Nenek Leha sahaja. Dia lebih tahu segalanya,” itu yang dibalas oleh Danish Aniq. Kemudian dia menyambung lagi.
“Aku orang luar. Tidak elok untuk
bercerita hal yang aku sendiri tidak pasti benar atau sebaliknya. Walau silap satu perkataan, berdosa di mata Allah. Sekiranya aku tertinggal atau menambah satu
perkataan yang tidak benar, aku sudah di
kira memfitnah. Kau tahu fitnah itu
lebih buruk daripada membunuh bukan?”
“Aku bingung dengan keadaan sekarang,”
kata Darwisyah, melankolis.
“Apa sebenarnya masalah kau?” Danish
Aniq cuba berbual. Jarak sekolahnya
semakin hampir. Sesekali langkah mereka
berdua dipintas oleh rakan-rakan lain yang juga ingin ke sekolah.
Mereka sudah mengetahui bahawa Darwisyah dan Danish Aniq bersaudara. Mereka tidak hairan apabila melihat mereka
berjalan bersama ke sekolah.
Lama Danish Aniq menunggu lontaran suara daripada Darwisyah. Tetapi dia hanya diam. Pandangannya terus ke hadapan.
“Aku tidak memaksa kau untuk bercerita kepadaku tentang apa masalah
kau. Terserah kepada kau sendiri samada
mahu atau tidak. Tapi tidak elok jika
terlalu memendam. Aku sudah anggap kau
seperti adik aku. Aku lapang dada jika
kau sudi bercerita kepadaku.”
Mereka sudah melepasi pintu gerbang sekolah. Sebelum berpisah arah, Darwisyah menjerit kecil ke arah Danish Aniq.
“Di dunia ini masih adakah abang
yang sudi menadah telinga mendengar cerita sedih daripada seorang yang bergelar
adik yang dibenci oleh saudara sendiri?”
“0.001 peratus, jika tiada. Yang
pasti aku bukan di antaranya. Aku
pendengar yang baik!”
Pertanyaan Darwisyah dibalas oleh Danish Aniq. Mereka tersenyum dan membawa haluan sendiri.
*****
“Tiba-tiba sahaja mama dan ayah aku beritahu yang aku akan bersekolah di
sini,” adu Darwisyah. Sayu.
“Sampai tamat tingkatan 5?”
“Aku tidak pasti.”
“Tidak pasti?” balas Danish Aniq
kembali.
“Ya. Bila aku tanya sampai bila aku
harus bersekolah di sini, mama dan ayah
aku hanya diam. Tetapi mereka ada
mengatakan bahawa tidak lama. Aku tidak
tahu ‘tidak lama’ bagi mereka itu selama mana.”
Masing-masing kembali diam.
Darwisyah akhirnya menceritakan apa yang sedang bermain di benaknya kepada
Danish Aniq.
“Kau tidak gembira tinggal di sini?”
Danish Aniq cuba menduga.
“Susah untuk aku katakan.”
“Mengapa?”
Pertanyaan Danish Aniq tidak di balas oleh Darwisyah. Dia seperti hilang kata. Perlahan sahaja langkah kakinya. Terik matahari yang menyegat seperti tidak
memberi kesan kepada mereka berdua.
Tudung sekolahnya berkibar-kibar disapa bayu.
“Aku dapat rasakan bahawa mama dan ayah aku sembunyikan sesuatu daripada
pengetahuan aku.”
Putusnya. Tegas sekali! Danish Aniq pantas berpaling melihat wajah
bujur Darwisyah. Pipi mulus gadis itu
sudah merah dipanah bahang mentari.
“Apa?” kata Danish Aniq dengan nada
terkejut.
“Aku dapat rasakan bahawa mama dan ayah aku sembunyikan sesuatu daripada
pengetahuan aku. Aku pasti. Aku pernah terdengar mama dan mak tok berbual
tentang perkara ini. Baru-baru ni
juga, ayah aku hubungi mak tok dan ada
sesuatu sedang berlaku di rumah sana,”
Darwisyah bercerita panjang lebar.
“Kau tahu apa yang mereka sembunyikan?”
Darwisyah hanya menggeleng. Buku di
tangan dipeluk erat.
“Ini yang mebuatkan air mata kau menitis ketika kali pertama aku menegur
kau?” teka Danish Aniq.
“Ya. Bukan itu sahaja. Aku sedih akan nasibku yang dibenci oleh bapa
saudara sendiri,” ujarnya. Suaranya mulai tersekat.
“Kau tidak boleh beranggapan begitu.
Mungkin Usu Roslan ada sebab mengapa dia bersikap begitu. Tidak mungkin dia benci kau,” Danish Aniq berbicara.
“Sedari kecil lagi Aniq. Sedari
kecil lagi Usu selalu marah-marah aku.
Kalau bukan marah pun, dia mesti
menyindir aku. Bukankah benci namanya?”
Darwisyah menyoal. Danish Aniq yang
setia mendengar tersenyum kecil lalu berkata,
“terlalu cepat kau buat andaian sebenarnya.”
“Ini bukan andaian Aniq. Ini apa
yang aku rasa selama ni,” dia menjawab
cepat kata-kata yang diluahkan oleh Danish Aniq.
“Bagaimana jika apa yang kau ‘rasa’ itu salah?”
“Erk...” Darwisyah tidak mampu
membalas.
“Seorang mukmin tidak boleh menuduh saudaranya tanpa
bukti yang kuat. Jika rasa yang cuba kau
katakan itu salah, itu sudah di kira
menuduh. Kau tahu, dosa menuduh orang lain yang tidak bersalah lebih berat dari
gunung yang tinggi. Seeloknya kau siasat
terlebih dahulu sebelum mengatakan ia betul atau salah. Negara pun ada undang-undang yang perlu kita
patuhi, apatah lagi agama.”
Darwisyah terdiam. Terpukul
dengan kata-kata Danish Aniq. Wajahnya
ditundukkan.
“Sebenarnya aku sangat bingung dengan apa yang sedang berlaku
sekarang. Aku tidak tahu apa punca semua
ini, yang membuatkan aku tercampak ke kampung ni.”
Suasana yang hening bebarapa saat kembali bersuara apabila
Darwisyah berbicara. Sauranya sayu. Riak-riak kecewa terkesan di situ.
“Mungkin ini semua untuk kebaikan kau.”
“Kebaikan? Apa maksud kau?”
Darwisyah yang tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Danish Aniq
bertanya lagi.
“Ya. Mungkin ibu bapa kau
mahukan kau hidup lebih berdikari. Di
sana, kau punyai segala-galanya. Kemewahan,
kesenangan dan sebagainya.
Seperti sekarang. Aku pasti kau
akan diambil oleh mama kau, bukan
berjalan pulang seperti ini atau menaiki bas sekolah. Betul?”
Gadis itu memandang wajah Danish Aniq penuh hairan. Dahinya berkerut.
“Mana kau tahu?”
“Kau kan anak manja!”
Bidas Danish Aniq. Nakal!
Menyedari dirinya dimainkan,
laju sahaja dia menghayun beberapa buah buku teks tebal di
tangannya. Bahu Danish Aniq menjadi
sasaran.
“Aduh!”
Suara mengaduh terluah dari mulut Danish Aniq. Dia mengurut-ngurut kasar bahunya. Kebas!
“Tak habis-habis nak kenakan aku!”
Wajahnya mulai masam.
“Aku minta maaf. Aku
bergurau tadi.”
Danish Aniq menarik nafas panjang sebelum menghembus kembali.
“Kau tertekan dengan situasi sekarang?” soalnya.
Tenang.
“Sedikit.”
Pendek jawapan yang diberi oleh Darwisyah.
“Janganlah terlalu fikir perkara yang tidak elok. Cuba ambilnya sebagai perkara yang positif.
Aku pasti fikiran kau akan lebih terganggu bila kau banyak memikirkan keburukan
daripada kebaikan. Percayalah!” ujar Danish Aniq.
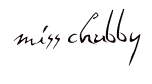


























Tiada ulasan:
Catat Ulasan